Abstrak
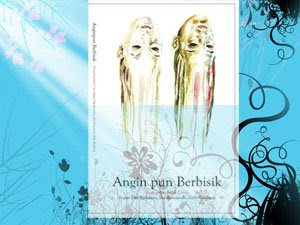
Selasa, Mei 20, 2014
Aku Merasakan Surga Dalam Pelukan Anak-anakku
Selasa, Juli 23, 2013
Puisi Langkah Seribu Bintang oleh Rike Diah Pitaloka karya Irwan Dwikustanto
Pembacaan puisi berjudul "Langkah Seribu Bintang" karya Irwan Dwikustanto oleh Rike Diah Pitaloka pada peluncuran antologi Angin Pun Berbisik di Gedung Kesenian Jakarta, 23 Januari 2008.
Jumat, Mei 27, 2011
Permainan Kata, Simbol, Asosiasi dan Bunyi
Oleh: Mohamad Sobari
Puisi ditulis tidak terutama untuk dipahami, melainkan untuk dinikmati. Para sarjana sastra, para kritikus, para penyair, dan mereka yang disebut ahli puisi, mungkin berpendapat lain karena mereka melihat puisi dari lebih banyak sudut pandang. Saya bukan bagian dari golongan itu.
Saya bersentuhan dengan puisi sebagai penikmat. Dengan sendirinya, meskipun saya tidak mengerti puisi tapi bisa menikmati puisi, seperti halnya banyak orang tak mengerti ujung pangkal persoalan musik, dan tak bisa memainkan instrumen musik apa pun, tapi mereka---juga saya---masih bisa menikmati keteraturan dan harmoni bunyi musik, dan makna-makna simbolis yang dikandungnya.
Ini karena puisi dan musik bersentuhan bukan dengan akal budi, dan rasionalitas, melainkan lebih dekat dengan dunia batin, dan perasaan manusia.
Puisi bisa dinikmati dengan mata wadak, karena komposisinya yang bagus, misalnya tersusun dalam bentuk segitiga sama kaki, atau segi tiga terbalik. Sebagian dalam komposisi piramida.
Selebihnya ada yang tampil dalam bait-bait biasa, yang membuat jiwa kita ikut hanyut dalam plastisitas permainan kata, permainan simbol dan bunyi dan ada kalanya kita mengikuti asosiasi antara kata, bunyi dan makna-makna yang tak jarang telah kita kenal secara akrab.
Ada bahkan puisi yang tak memperlihatkan komposisi, misalnya puisi satu baris kalimat, karya penyair Toba, Sitor Situmorang, berjudul "Malam Lebaran"
Bulan di atas kuburan
Ada pula puisi yang bisa dinikmati dari segi komposisinya yang tak terlalu "lazim", yang merupakan hasil "perjuangan" mencari kebaruan-kebaruan, yang kemudian diikuti banyak penyair lain, seperti dapat dicontohkan pada karya-karya Sutardji Chalzoun Bachri.
Sementara itu permainan kata dan bunyi, yang membuat kita mengasosiasikannya dengan kata dan bunyi lain---yang bisa saja tak harus sama dengan apa yang dimaksudkan Tardji sendiri---dapat ditemukan dalam bunyi "ngiau" yang mudah kita terka simbol atau bunyi apa. Patut dicatat bahwa pada dasarnya puisi-puisi Tardji disebut puisi "gelap" : puisi abstrak, simbolik dan tak mudah ditebak maknanya.
"Angin Pun Berbisik": Kumpulan Sajak Cinta, yang ditulis oleh satu keluarga "aneh" yang semuanya penyair--- atau semua berusaha dan mencoba menjadi penyair---ini pula pelan-pelan membawa saya ke satu kenikmatan kenikmatan lain. Ada kenikmatan bunyi, ada kenikmatan kata dan symbol, yang mengikat dan mempertautkan kita dengan perasaan dan pengalaman masa lalu kita. Tapi sebagian dengan jelas mempertautkannya dengan sejarah dan pengalaman masa lalu para penyair ini sendiri.
Sebetulnya saya tak harus mengatakan bahwa sajak bukan lahir dari rindu yang melankolik, dan ketika kita yang sedang rindu itu melihat bulan langsung lahir sebuah sajak. Sajak yang lahir karena melihat bulan, atau menghayalkan bunyi ombak dan watak lautan, biasanya hanya menjadi "sajak-sajakan" yang dangkal dan hampa dari makna. Sajak yang intens selalu lahir dari sejarah kegetiran, dari perjuangan, dan dari makna-makna terdalam, yang menyentuh penghayatan dan dunia nilai di dasar kehidupan manusia.
Sajak "Nisan", karya Chairil Anwar, misalnya, lahir dari kegetiran hidup seorang cucu yang kehilangan sang nenek yang sangat dicintainya. Juga karya Chairil lainnya: "Tak Sepadan" misalnya.
Buku ini memperlihatkan dengan nyata, dan secara simbolik menyiratkan penghayatan dan pengalaman sejarah yang intens di dalam hidup para penyairnya. Tapi saya hanya bisa menampilkan sebagian yang saya tangkap dengan cepat, Ini yang berhubungan dengan kata -kata dan simbol di baliknya;
Kudengar entah suara siapa
Melengking melantunkan doa
( "Angin Pun Berbisik" 4)
Kudengar angin pun berbisik
Hampa mendera di antara kita:
Sepi, dan...
Semakin menggeletar ketika angin berlalu
(Dari judul yang sama, penyair yang sama).
Cinta dan rinduku padamu
Hanya dewa yang menyimpannya
( "Cintaku Padamu").
Namun dalam syair doaku-doaku
Namamu,masih mewarnai guratannya
("Angin Pun Berbisik" 5)
Sajak-sajak ini memberi kenikmatan kita, dan kita diberi kebebasan untuk memaknainya secara subyektif, sesuai dengan batas pengalaman dan penghayatan kita atas hidup, ketakutan, rasa cemas dan doa, yang mungkin membebaskan kita dari rasa takut dan kecematasan itu.
Ataukah doa hanya respons latah? Mengapa doa yang tampil? Usaha mencari pemecahan masalah secara mudah, dan bahkan yang termudah dari semua yang bisa ditempuh manusia? Ataukah doa merupakan cermin kedalaman iman, ketulusan dan kegigihan meluhurkan Tuhan, dan yang akan dengan sendirinya membuat segala masalah lenyap, selesai, dan tuntas?
Saya tak ingin menjawab persoalan-persoalan ini untuk membiarkannya menjadi bagian dari kompleksitas sajak-sajak di dalam buku ini. Selebihnya saya pun merasakan indahnya ungkapan kata-kata di bait-bait terakhir sajak Irwan, dengan judul "Cemburu" 2, berikut;
Sedang rembulan di tanangmu belum jua membelah
Malam untuk dibaringkan
Pada bantal yang selalu basah
Karena air mata tak cukup mengucap cinta
Saya merasakan ungkapan-ungkapan Irwan yang belum pernah saya baca sajaknya sebelum ini, begitu kuat. Namun tentu saja ada yang berakhir lemah, kurang daya dan tak punya gema, mungkin karena salah memilih kata atau ungkapan?
Ia tak punya pilihan
Cinta menjadikannya luruh pada nasibnya;
di mana perempuan selalu menerimanya;
sebagai mimpi yang harus dirajutnya
Saya merasakan ungkapan ini seperti sebuah pidato yang membosankan. Mungkin karena penyairnya belum terlalu terlatih dan masih sibuk melawan gangguan kedangkalannya sendiri?
Siti,Atmamiah, dalam puisi "Gubah" mengingatkan kita pada lagu tahun 1970-an "Blue blue my love is blue", ketika ia berdendang:
Dan langit berubah menjadi puisi
Hidupku
Untuk kau gubah kembali
Dengan biru cintamu
Dalam puisi "Ibu", Siti berkata;
Ibu,
Kupinjam surgamu
Melebar legam tubuhmu
Ia menyampaikan pada kita makna simbolik Ibu sebagai pemilik, atau pembawa (?) surga, sebagaimana kita kenal baik ungkapan" surga di bawah telapak kaki ibu"
Dalam puisi "Kepada Adam", kita disuguhi oleh Siti, penghayatan atas pengalaman sejarah, tapi tanpa kegetiran, tanpa rasa duka. Pengalaman dan sejarah di sini tampil dalam wajah rutinitas yang datar, dan mungkin juga hambar karena tanpa sekeping pun unsur dramatik di dalamnya.
Aku adalah waktu yang rindu
Berbaring dan mengenang
Lembar demi lembar
Cerita lama
Ketika malam tiba-tiba
Menjadi pagi
Tetapi di dalam "Ketika Putri Kecilku Melihat Bulan" kita disuguhi asosiasi yang begitu alamiah melalui cara pandang kanak-kanak;
"Mama, aku melihat bola
Di atas sana
Putih warnanya
Seperti bola mainanku"
Dan Siti pun menjelaskan makna asosiasi yang lain, hening itu identik dengan sujud, atau sebaliknya: sujud adalah momen keheningan.
"Tuhan telah menjaganya
Dan heningnya itu
Adalah sujudnya"
Dalam "Angin" kita simak uangkapan Zeffa mengenai angin sebagai nada indah dan suara merdu' yang terasa seperti sebuah reportase jurnalistik.
Angin..
Tidak akan pernah habis, ceritamu
Setiap hari berlari denganku
Nada indah dan suara merdu
Untuk alam dan teman-temanku
Dalam puisi "Pasar" Zeffa memberi kita sebuah metafora' Pasar
Banyak orang bertukar barang
Sedikit orang bertukar senyum
Seorang anak ingin membeli senyum
Tapi tak ada yang menjual senyum
Sedihnya..
Dan kita pun dibuatnya berpikir, bahwa pasar, dunia ekonomi yang memang angkuh, yang menghormati manusia, dan menentukan derajatnya sesuai dengan jumlah kekayaan (uang) yang dimilikinya, memang tak pernah merasa perlu tersenyum.
Kita belajar dari puisi Zeffa bahwa banyak hal bisa dibeli. Tapi senyum tidak. Di sini, sekali lagi, saya menikmati kaitan antara permainan kata, simbol dan bunyi, dan asosiasi antara makna suatu kata dengan suatu jenis bunyi,
Saya dan buku puisi ini berdialog dan saling melengkapi. Saya bersyukur sempat meluangkan waktu untuk menikmati indahnya kata, symbol, bunyi dan asosiasi, yang seolah berloncatan secara dinamik dalam dunia nilai yang tak kasat mata.
Anggrek Neli Murni II A No.C.25 Slipi, Jakarta Barat
Dikutp dari: http://www.mitranetra.or.id/puisi/index.asp?mnu=1
Rabu, Mei 18, 2011
Makna Senja
Luka seorang lelaki adalah senja
Yang temaramnya menjerit lirih
...
Puisi berjudul Luka Seorang Lelaki itu adalah karya Irwan Dwi Kustanto, seorang penyandang tunanetra. Bersama sejumlah puisi lain, puisi itu dikumpulkan dalam buku Angin pun Berbisik. Antologi puisi itu diluncurkan sekaligus didiskusikan di Gedung Kesenian Jakarta pada Rabu lalu.
Dalam puisi-puisi di buku ini, pria berumur 42 tahun ini mencoba memaknai apa yang dialaminya dengan caranya sendiri, antara lain senja. Irwan menggambarkan senja dalam bentuk bunyi atau suara, yang merupakan salah satu sarana bagi tunanetra untuk berinteraksi.
Hal yang sama ditemui pada puisi-puisinya yang lain. Salah satunya adalah Rinduku padamu.
...
Rinduku padamu: Semerbak mawar
Tak terurai walau merah kelopaknya menggema
Tak terserap walau wanginya menebar
...
Menurut penyair Joko Pinurbo, yang menjadi pembicara dalam bedah buku tersebut, asosiasi yang dihadirkan Irwan dalam sajak-sajaknya memiliki kekhasan sendiri. "Ia memiliki kejujuran yang butuh keberanian mental. Padahal banyak penyair lain yang menyembunyikan perasaannya," kata Joko.
Puisi Rinduku padamu, kata Joko, menunjukkan bagaimana hal yang bersifat individual bisa jadi penerangan bagi orang lain.
Irwan mengakui puisi-puisinya berangkat dari pengalaman pribadi. "Saya hanya mengungkapkan apa yang saya rasakan," ujar ayah tiga putri ini. "Hidup ini indah. Tinggal bagaimana kita menyikapinya," ujarnya.
Pengalaman hidup Irwan yang tidak bisa melihat sejak usia 9 tahun terbilang cukup menyedihkan. Tidak jarang ia mendapat perlakuan kasar dari orang lain. Salah satunya adalah ketika ia dikeluarkan dari tempat kuliahnya di sebuah kampus yang mendidik calon guru di Jakarta. Alasannya, calon guru tidak boleh cacat.
Tak menyerah begitu saja, Irwan kemudian melanjutkan kuliah dan berhasil meraih gelar sarjana dari Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Besarnya perhatian teman-temannya membuat Irwan semakin kuat. "Saya punya sahabat yang suka membacakan buku untuk saya," ujarnya.
Selain puisi-puisi Irwan, buku setebal 164 halaman itu juga memuat puisi karya istrinya, Siti Atmamiah, 42 tahun, dan putri sulungnya, Zeffa Yurihana, 11 tahun. Karya Zeffa juga cukup menarik. Lihat saja puisi Pasar yang merupakan metafora terhadap kondisi pasar.
...
Banyak orang bertukar barang
Sedikit orang bertukar senyum
Seorang anak ingin membeli senyum
Tapi tidak ada yang menjual senyum,
Sedihnya...
Zeffa mengaku ayahnyalah yang mengajarinya menulis puisi. Puisi yang ditulisnya ketika berusia 9 tahun tersebut merupakan apa yang ditemuinya ketika pergi ke pasar bersama ibu. "Ayah mengajarkan untuk menulis apa yang ada di hati dan apa yang dirasakan," ujar siswa di Madrasah Ibtidaiyah Al-Azhar Bandung, Tulungagung, ini.
Menurut akademisi sastra Melani Budianta, puisi Pasar itu memberikan kita suatu pelajaran berarti: pasar yang merupakan tempat sosial telah kehilangan nilai sosialnya. "Semuanya hanya didasarkan pada kepentingan," ujarnya.
Seusai bedah buku, malamnya sejumlah acara seni ditampilkan untuk menandai peluncuran buku itu. Ada kolaborasi Irwan dengan pianis Marusya Nainggolan, pertunjukan teater, pembacaan puisi oleh Dewi Lestari, Rieke Dyah Pitaloka, Joko Pinurbo, dan Zefra, serta musikalisasi puisi oleh mahasiswa tunanetra.
TEMPO Interaktif, Jakarta:
Sumber: http://www.tempointeraktif.com/share/?act=TmV3cw==&type=UHJpbnQ=&media=bmV3cw==&y=JEdMT0JBTFNbeV0=&m=JEdMT0JBTFNbbV0=&d=JEdMT0JBTFNbZF0=&id=MTE2MzA5
Kamis, April 21, 2011
Penghargaan Irwan Dwi Kustanto dan Habibie Afsyah

Penyandang tunanetra Irwan Dwi Kustanto dan tunadaksa Habibie Afsyah mendapat penghargaan dari Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo pada saat membuka Pesta Buku Jakarta ke-20 di Istora Senayan, Jumat dua pekan lalu. Keduanya dinilai berprestasi meski menyandang kekurangan. Irwan telah menerbitkan kumpul an puisi berjudul Antologi Puisi Angin pun Berbisik. Adapun Habibie, 22 tahun, menulis buku Kelemahanku Adalah Kekuatanku.
Sumber: http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2010/07/12/ALB/mbm.20100712.ALB134043.id.html#